Pendahuluan:
Sebuah Melodia
Tulisan ini adalah monogram yang tidak ada artinya
samasekali. Namun saya merasa perlu mengkajinya kembali. Lebih-lebih monogram
ini merupakan anagram yang diilhami oleh Voltaire, yang menjadi sangat kondang
dengan anagramnya ketimbang aslinya.
|
S
|
elain
itu, monogram ini merupakan usaha untuk memberikan gambaran lebih terperinci
tentang suatu peristiwa sejarah, yang karena penyajiannya yang jauh dari
lengkap sehingga dia bagaikan monster yang menakutkan. Padahal, dia adalah suatu
peristiwa paling dramatis, aromatis, melankolis, dan juga romantika revolusi
dan sejarah peradaban manusia. Dia memberi inspirasi dan ilham bagi mereka yang
mendambakan suatu ideologi dan bukan elitis melainkan populis, suatu keagungan
jagat raya yang mencerminkan manusia seutuhnya dalam gelarnya sebagai homo ludens, yang dengan nalar
menjadikannya homo faber, anak alam
yang menaklukkan dunia, membebaskan dari segala bentuk kemiskinan, penindasan,
pemerasan dengan segala efek sampingan.
Melodia
adalah anagram penuh janji, cita-cita, dan impian-impian masa datang bagi
mereka yang percaya pada nyanyi dan lagu merdu yang mengalun darinya. Ini
bukanlah paksaan untuk memercayainya dan jangan percaya kalau kemudian Anda
meyakininya, karena memang selalu ambigu, berbau duopoli. Namun yang utama bagi
saya, monogram ini merupakan suatu uji coba dan usaha untuk mencari kebenaran
dari realitas yang bersifat empiris dan bahkan mungkin radikal, walau usaha ini
tidak terpusat pada politik—di mana radikal diartikan sebagai setiap usaha bagi
setiap orang yang ingin mengubah tatanan sosial secara menyeluruh sampai ke
akar-akarnya karena radikal berasal dari bahasa Latin, radix, yang bermakna akar atau root.
Dalam
sejarah, pembentukan bangsa sangat rumit. Namun sejak kemunculan gerakan
rasionalisme, nasionalisme menjadi salah satu gerakan yang menjadi sentimen
kesadaran yang membahana, merasuk dalam jiwa publik dan kehidupan perorangan.
Dia bisa dibilang satu faktor yang menonjol atau bahkan paling menonjol dalam
sejarah umat manusia. Melihat pada zamannya bisa dibilang nasionalisme adalah
gerakan yang dimasukkan dalam kategori modern, yang mewabah ke seluruh penjuru
dunia dan hidup sentosa dalam kehidupan sosial dan organisasi umat manusia.
Dalam kebangkitan kesadaran nasionalisme itu, manusia meneropong masa lalu
dengan segala kekeliruan sejarahnya.
Nasionalisme
bangkit sebagai kekuatan yang sangat dominan di Eropa Barat dan Amerika Utara.
Harus diakui, revolusi di Amerika dan Perancis merupakan inti pertama wabah
nasionalisme. Kemudian, pada permulaan abad ke-19, wabah dari jantung Eropa itu
merambah ke seluruh daratan Eropa. Abad berikutnya dia merambah ke Asia dan
Afrika. Dengan kelahiran berbagai negara di Amerika Latin, wabah nasionalisme
juga merambah daratan itu. Dunia setuju bahwa abad ke-19 merupakan abad
nasionalisme di Eropa dan abad ke-20 di Asia.
Dulu,
masalah nasionalisme menyatakan secara tidak langsung tentang negara dan bangsa
berdasar prinsip geografi. Pada era nasionalisme modern pengertian tersebut
mengalami perombakan. Bangsa disatukan oleh keinsyafan, kesadaran, state of mind, untuk hidup bersama bukan
atas rekayasa intimidasi dan penindasan alat kekuasaan, keserakahan,
kepongahan, ketamakan penguasa. Ingat masa kejayaan Yunani dengan peradaban
Sparta dan Athena. Kejayaan Kristen, Islam, Mongol, dan lain-lain. Kesetiaan
politik, sebelum era nasionalisme, bukan didominasi oleh kebangsaan, juga bukan
oleh peradaban, melainkan oleh keyakinan, kepercayaan agama. Belakangan, ketika
era Renaisance dan Klasikisme, pada zaman Yunani dan Romawi, peradaban menjadi
norma universal yang dipandang sebagai acuan untuk semua orang dan sepanjang
waktu. Lebih ke belakang lagi, peradaban Perancis menjadi norma standar di
seluruh Eropa. Hanya pada akhir abad ke-18 peradaban baru diakui sebagai sumber
kesetiaan, yang bermuara pula pada nasionalisme, yang antara lain mengedepankan
prinsip bahwa semua orang hanya dapat diajar dalam bahasa ibunya, bukan dalam
bahasa dari peradaban lain. Dari akhir abad ke-18 itu terjadi perombakan dalam
sistem pendidikan, kehidupan gayung bersambut dengan perombakan sistem
kenegaraan loyalitas bangsa. Perombakan itu dibantu oleh para penyair, seniman,
dalam penciptaan budaya nasionalisme, merombak bahasa nasional menuju ke bahasa
yang lebih tinggi kualitasnya dalam dunia sastra. Terjadi perombakan di segala
bidang yang akhirnya bermuara pada spirit
nasionalisme. Melemahnya dominasi agama, sistem feodal, sektantisme, dan
sebagainya mempercepat lahir dan tumbuh wabah nasionalisme. Dia dipercepat oleh
rasionalisasi pendidikan, perkembangan ekonomi yang saling tergantung, yang
membutuhkan teritori yang lebih luas, diikuti kelahiran kelas menengah dengan
usaha-usaha mereka yang bernuansa kapitalistik. Perkembangan itu menciptakan
negara dengan kesatuan wilayah dengan sistem konsentrasi politik dan ekonomi,
yang juga merupakan spirit kelahiran
nasionalisme. Dalam masalah nasionalisme, Indonesia tertinggal dua abad
lamanya. Itu pun lahir dari rekayasa balas budi, yang disponsori oleh penjajah
Belanda dengan bom waktu terselubung: “politik balas budi.”
Pendek
kata, pengaruh ajaran baru tentang nasionalisme merombak banyak tatanan dan
dominasi tradisi lama, termasuk cara berpikir, dari dua ribu tahun kejayaannya.
Dalam revolusi pemikiran itu, kita bisa sebut John Milton dengan konsep liberty, John Locke, Thomas Jefferson,
Thomas Paine, Jean Jacques Rousseau, Johann Herder. Slogan termasyhur liberty, egality, fraternity ditambah
dengan deklarasi hak asasi manusia menjadikan nasionalisme wabah yang mendunia.
Tentang
wilayah bahasa: bahasa merupakan salah satu akar rumput bangsa. Namun tidak mutlak.
Orang bisa saja memilih bangsa tanpa harus ingat akan akar rumputnya. Dalam
sejarah kelahiran bangsa, Indonesia termasuk salah satu yang paling unik di
dunia. Mustahil diambah dengan mukjizat. Bangsa lahir karena sumpah. Orang
Yunani, Yahudi, menjadi bangsa karena akar rumput misi menjadi peradaban,
budaya, dan tradisi. Semua tersimpul dalam keseharian kehidupan mereka yang
disebut etos, dari etika. Etika bangsa, etos bangsa. Belakangan orang sering
mempergunakan maniak, crazy, atau holism: technocrazy, workholism, communistomaniac, dan sebagainya
memberikan indikasi kecenderungan akan etos yang berlebihan. Semua itu mungkin
berkonotasi positif, namun yang tidak berakar rumput dalam wilayah, bangsa, dan
bahasa ini.
Negara
Kesatuan Republik Indonesia sejak lahir memang tidak pernah utuh; keretakan
silih berganti menghiasi sejarahnya yang sudah lebih dari setengah abad, mulai
dari federalisme, separatisme, renegadisme, sampai vandalisme tradisi, seni,
budaya, dan peradaban. Hal itu ditambah dengan kemelelehan nasionalisme, yang
memang kurang mempunyai akar rumput yang kuat. Kelemahan penegakan hukum
menyebabkan negara yang sepertinya menganut paham demokrasi ini terjerumus ke
dalam kediktatoran penguasa ala Napoleon Bonaparte. Itu menyebabkan timbulnya kesewenang-wenangan,
ketidakadilan. Manusia kehilangan hak sebagai manusia. Banyak peristiwa
mengungkapkan kenyataan bahwa warga diperlakukan tidak lebih baik dari ternak.
Dibakar hidup-hidup karena mencuri motor, dibunuh karena dicurigai sebagai
dukun santet. Karya seni Tisna Sanjaya dari Bandung dibakar karena dianggap
sampah oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Berbagai kekerasan dan penganiayaan
para siswa STPDN, Jatinangor.
Semua
itu merupakan bukti yang membenarkan prediksi Pythagoras atau Konghucu yang menyatakan
sejak lahir manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat jahat. Di sisi lain,
yang terlanjur berbuat jahat dan takut menanggung akibatnya, gencar
mempopulerkan rekonsiliasi nasional, yang diharapkan mampu menyelesaikan
berbagai konflik dan beda pandangan politik dan ideologi untuk bersama-sama
membangun bangsa. Mereka menilai, mengangkat harkat bangsa itu dengan cara
duduk bersama, mempertemukan berbagai pandangan. Itu adalah jargon politik yang
sudah basi. Mengangkat harkat bangsa bukan dengan duduk bersama, melainkan
berkarya bersama sesuai dengan bakat, minat, dan cita-cita. Manusia Indonesia
bisa mengangkat diri melalui kerja, baik yang bersifat individualistik maupun
komunal, ditunjang oleh etos kerja dalam keluarga. Bangsa harus diubah dari konsumtif
menjadi produktif. Akar harkat bangsa itu dengan karya, dengan kerja keras yang
dimulai dari perseorangan. Harus diingat, kerja bukanlah kejahatan kemanusiaan.
Dengan kerja apa saja yang bermanfaat, pertama orang menghargai jerih payahnya
sendiri, bau keringatnya sendiri. Kedua, lahir rasa dan kesadaran menghargai
kerja orang lain. Ketiga, tumbuh kesadaran membina keluarga dengan kerja
sebagai budaya. Keempat, keluarga yang mapan menciptakan kedamaian keluarga
yang berbuntut hubungan yang serasi dan sederajat dengan keluarga lain. Kelima,
kalau persoalan keluarga dan antarkeluarga bisa diatur, budaya ketertiban
masyarakat semestinya akan tercipta karena punya akar rumput yang kukuh. Dan
budaya seperti itu bisa meningkat sampai ke jenjang yang lebih tinggi.
Kalau
akar permasalahannya bisa diatasi semestinya berbagai tabiat buruk dalam
masyarakat juga bisa diatasi. Sifat malas, serakah, berdusta, kejam, dan
sebagainya menjadi terkesampingkan. Dalam hal ini, ajaran sang Buddha dan
ajaran-ajaran kepercayaan lain yang positif akan sangat relevan dan membantu.
Bangsa
ini makin hari bukan menjadi kian dewasa, justru menjadi makin beringas, kejam,
serakah, dan sifat buruk yang lain. Semua tercermin dalam polah masyarakat yang
bisa ditelusuri baik dalam surat kabar maupun televisi. Penodongan,
pemerkosaan, pembunuhan, korupsi, pembobolan bank, manipulasi, KKN, dan
kebobrokan masyarakat yang lain. Sinyalemen van Geldener bahwa bangsa ini
adalah bangsa kuli sudah lama menjadi kenyataan. Kalau sebelum perang kita jaya
dalam berbagai hasil produksi pertanian, perkebunan, dan pertambangan serta
menjadi pengekspor kelas dunia, kini hanya menjadi sejarah. Ekspor manusia ala
Las Casas abad ke-17-18 terulang pada milenium ketiga ini. TKI dan TKW ke luar
negeri menjadi primadona kesibukan yang mendatangkan rezeki. Tidak peduli bahwa
sebagian di antara mereka diperlakukan tidak lebih dari budak dan ternak.
Sia-sia Multatuli mengorbankan seluruh hidupnya demi manusia Nusantara. Dia
hanya mendambakan kita menjadi manusia. Manusia yang berhasrat untuk hidup bersama
menjadi bangsa ala Ernest Renan: bangsa Indonesia.
Karena
itulah, perlu menelaah tokoh Charles Darwin yang mengajarkan bahwa untuk
membuktikan kita ini manusia, kita harus bekerja. Hanya dengan kerja kita
menjadi manusia sejati. Manusia sejati adalah perubahan dari homo sapiens menjadi homo ludens. Dalam proses menjadi homo ludens, manusia langsung atau tidak
langsung belajar dari lingkungan, memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan
harkatnya. Kalau demikian, maka manusia akan menapak lebih tinggi, yaitu
menjadi homo faber, manusia yang
mampu mencukupi kebutuhan sendiri dan lingkungannya. Kalau berhasil, manusia
akan berpikir secara rasional dan mulai memilah-milah kebutuhan dan jadilah
manusia sebagai homo economicus
sejati dengan prinsip yang dihafal dari anak SD sampai mahasiswa: tenaga sesedikit
mungkin, hasil sebesar mungkin.
Namun
untuk menyelesaikan berbagai kepentingan di luar itu, masalah hubungan
antarbangsa, antarkelompok, kedaulatan batas wilayah, dan sebagainya, lahirlah
manusia homo economicus itu menjadi
mahkluk baru yang dikenal dengan nama homo
politicus. Di sini watak manusia terbelah menjadi dua. Dengan politik
manusia membela hak dan kepentingannya, dengan politik itu juga manusia
merampas dan merampok hak dan kepentingan manusia lain. Ingat selalu pesan
salah seorang dari banyak presiden terbunuh negeri adidaya dengan konsep
demokrasinya yang agung, “demokrasi”—Amerika Serikat. John Fitzgerald
Kennedy berpetuah beberapa waktu sebelum mati ditembak warga negaranya sendiri,
“Dalam politik tidak ada sahabat sejati. Yang ada hanyalah sekutu. Kita bisa
memaafkannya, tetapi tidak bisa melupakannya.”
Apa
yang dipetuahkan John Fitzgerald Kennedy sama sekali sempurna. Benar,
mutlak, bahkan bisa dijadikan dogma atau doktrin bagi siapa saja yang mau
berkecimpung dalam dunia politik. Contoh konkret adalah dunia perpolitikan di
Tanah Air. Tidak salah dan malu kita menerima petuah dari tokoh Malaysia, Mahathir
Mohamad, bahwa untuk pembangunan negara dan bangsa diperlukan syarat mutlak:
stabilitas politik. Sama sekali benar nasehat Ben Mboi, bekas Gubernur dan anggota
DPA, yang mengatakan, “Janganlah bereksperimen dengan masyarakat dan negara.”
Dan model coba-coba begini, bangsa kita sudah kenyang, dan itu berarti kita
belum paham.
Kita
belum menjadi bangsa yang cerdas, baik dengan perkataan maupun dengan
perbuatan. Mari kita cermati nasehat pemenang Nobel Sastra asal Mesir. Mahfouz
Naguib bilang, “Engkau bisa tahu apakah seseorang cerdas dari jawabannya. Dan
engkau bisa tahu apakah seseorang bijak dari pertanyaannya.” Sulit dibuktikan.
Lebih-lebih dalam dunia politik. Semua berbau busuk dan bernuansa dekadensi
moral. Namun masih ada orang yang waras di antara orang yang gila. Simak kata
sutradara dari Jepang, Akira Kurosawa, yang berkilah, “Di dunia gila, hanya si
gila yang waras.” Apakah ketika bangsa kita berjuang tahun 1945 dulu termasuk
bangsa yang gila, gandrung, dan maniak kemerdekaan? Bisa jadi ya. Yang patut
dicatat adalah ajarah tokoh hak-hak sipil yang punya nasib seperti John Fitzgerald
Kennedy, Martin Luther King Jr, bahwa kemerdekaan takkan pernah diberikan
secara sukarela oleh penindas, tetapi harus dituntut oleh mereka yang
tertindas. Lebih afdol lagi kalau kata “dituntut” itu diganti “direbut,” sebab
memang situasi dan kondisi waktu tahun 1945 memungkinkan tindakan demikian. Hal
itu berkat pelajaran dari orang Amerika juga yang mengajari, “Melewatkan
kesempatan adalah kebodohan.”
Lalu,
bagaimana dengan situasi dan kondisi negara ini? Korupsi merajalela. Dalam
kajian luar negeri, Indonesia termasuk negara paling korup di dunia. Membantah
sama artinya dengan membenarkan. Beras (untuk warga) miskin dikorup. Bantuan
dari luar negeri diembat. Jatah rumah sakit dikemplang. Harga makanan ternak
disulap. Pendek kata, awur-awuran.
Bahkan bahasa pun dikorup, seperti yang dicermati George Orwell, penulis dari
Inggris, yang mengedepankan pendapat, “Jika pikiran mengorupsi bahasa, bahasa
pun sanggup mengorupsi pikiran.” Apalagi korupsi benda yang bernilai jual. Baca
novel Korupsi karya Pramoedya Ananta
Toer; yang dimulai hanya mencuri beberapa lembar kertas dari kantor. Kenikmatan
itu kemudian menjadi budaya dan darah dagingnya. Dan, jadilah kemudian dia
koruptor dan dia menikmati predikat barunya.
Dan,
sedikit berbicara filosof, adakah beda antara kenikmatan dan kebahagiaan itu,
atau keduanya saling tergantung, saling mengisi, saling menunjang? Masih dalam
nuansa filosofis, renungkanlah kesimpulan brilian dari tokoh dualis terbesar di
dunia, Immanuel Kant, “Kebahagiaan bukanlah ideal akal, melainkan imajinasi.”
Untuk mengerti ajaran itu, kita perlu mendalami ajaran Immanuel Kant lebih
dalam. Sayang, bangsa ini bukan science
maniac, gila ilmu. Bangsa ini adalah bangsa yang liat, bersikukuh dengan
kekayaan rohani leluhur. Maksud saya, jika dia Islam, bukan Islam sejati. Kalau
dia Kristen, bukan Kristen sejati. Kalau dia Hindu, bukan Hindu sejati.
Kesempurnaan dia sebagai manusia dilengkapi dengan bekal tradisi leluhurnya.
Keyakinannya tidak totaliter seperti tokoh eksistensialisme Sorem Aabye
Kierkegaard yang yakin bahwa kalau mau eksis bertindaknya secara menyeluruh.
Selagi percaya dia lebih dari siapa pun, selagi tidak percaya dia pun lebih
dari siapa pun. Menurut pendapat dia, setiap manusia mempunyai tantangan
dunianya sendiri. Tidak ada kekecualian, termasuk dirinya sendiri. “Aku tertawa
dengan satu muka, aku tersedu dengan muka yang lain.”
Sindiran itu adalah cermin keadaan
secara menyeluruh proses yang ada di Indonesia sekarang ini, yang kalau
dicermati intinya merupakan bom waktu—warisan politik etis yang diselewengkan.
Dan, Pramoedya Ananta Toer adalah seorang pengarang yang berhasil, bahkan
sangat berhasil. Saya termasuk penulis yang sangat berhasil—berhasil gagal.
Anda bisa simak dan baca apa yang saya tulis. Dan, Anda akan rasakan benar
keberhasilan saya yang gagal itu. Justru itu kritik, maki, umpat, tumpahkan
semua. Dan saya akan selalu sampaikan terima kasih, hanya dengan catatan kecil
sebagai permohonan: tulislah lebih baik dari saya.
Soesilo Toer
"PRAM DARI DALAM" karya SOESILO TOER
Penerbit: Pataba Press
Penyunting: Gunawan Budi Susanto
Cetakan pertama: Februari 2013
Cetakan kedua: Februari 2015
Tebal buku: xii + 286 halaman, 14 x 21 cm
ISBN: 978-602-17414-2-9
Harga: Rp 70.000,00 (Belum termasuk ongkos kirim)
Pemesanan:
* Purwokerto dan sekitarnya: Yuli Rm (081568241918)
* Cirebon dan sekitarnya: Hermawan Widodo (081914020214).
* Semarang dan sekitarnya: Kang Putu (087731631118).
* Jogja dan sekitarnya: Marheriyanto, Fakultas Teknologi Pertanian UGM Jogja (081328274794) / Senja Mulyana (085721364525/082138878011).
* Mojokerto dan sekitarnya: Rockhand (089619090001)
* Karawang dan sekitarnya: Khamid Istakhori (085695622555)
* Malaysia: Zaidi Musa, Kedai Hitam
Putih (+60123840415)
* Jakarta dan
sekitarnya: Yohana Sudarsono: (085693269444/089677578419) / Koesalah Soebagyo
Toer Jl. Turi III No 27 RT 05/10
Kemiri Muka, Beji, Depok 16423 (087785067160)
#Pemesanan dari berbagai kota lain di
Indonesia bisa ke Benee Santoso
Jalan Sumbawa Nomor 40 Kelurahan Jetis, Kota Blora, Jawa Tengah
Telepon +6287742070671/+6285711631124 BBM: 537CB695 WA: 089653169450 Wechat/Line : ben_kim13
Jalan Sumbawa Nomor 40 Kelurahan Jetis, Kota Blora, Jawa Tengah
Telepon +6287742070671/+6285711631124 BBM: 537CB695 WA: 089653169450 Wechat/Line : ben_kim13
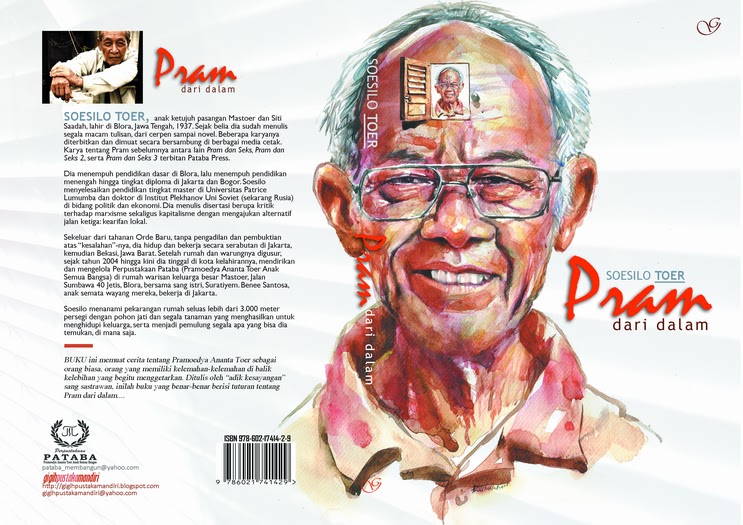
Tidak ada komentar:
Posting Komentar